“Kamu kenal Rifki dari mana?”
Suara Nino agak melengking begitu dia selesai mengecek akun twitterku. Saat ini kami berada di area Taman Kampus Teknik, kampusnya Nino. Tidak terlalu banyak orang, hanya kami dan beberapa mahasiswa yang sedang sibuk dengan laptopnya masing-masing.
Di Universitas kami, Taman Kampus Teknik memang yang paling nyaman. Selain baru, lokasinya juga tidak jauh dari kampus kedokteran, Kampusku. Beberapa pohon akasia membuatnya teduh dan nyaman. Juga air mancur yang didesign dengan begitu apik di tengah-tengah taman.
Kadang aku iri. Kenapa taman kampus kedokteran tidak sekeren kampus Teknik!
Tanganku mengambil alih ponsel dari tangannya, mengeluarkan aplikasi twitter dan memasukannya ke dalam tas. “Kamu gak tahu? Kami kan satu SMA.”
Mata Nino memicing. Aku tahu betul saat ini Nino sedang mencurigaiku, ah Nino memang pacar pencemburu nomor satu!
“Terus, ngapain kalian ngomongin tentang latihan Sanggamara?”
Omong-omong, Sanggamara adalah nama klub pecinta alam yang diikuti Rifki. Entah dengan alasan apa, tiba-tiba Rifki mengajakku untuk mengikuti acara Mendaki Santai. Acara Sanggamara yang ke … sekian kalinya. Aku juga tidak begitu tahu tentang acara itu, tapi apa salahnya mencoba dan memenuhi undangan?
“Aku diajak Mendaki Santai ke Gunung … Gunung mana ya? Aku lupa.”
Seperti dugaanku. Nino tercengang mendengar bagaimana aku menjawab pertanyaannya dengan begitu santai. Aku cukup mengenal Nino selama dua tahun menjadi pacarnya. Dan Nino sama sekali tidak akan mengijinkan aku untuk mengikuti ajakan Rifki.
Jangankan naik gunung, pergi liburan ke Pulau Seribu bersama teman-teman sekelas saja tidak diijinkan. Selain pencemburu, Nino juga posesif. Ih, untung saja aku cinta sama dia.
“Kamu gak bercanda kan, Git?”
“Bercanda gimana?”
Sepertinya sikapku yang dibuat sesantai mungkin sedari tadi membuatnya agak jengkel. Dengan lembut Nino menarik bahuku sehingga aku tepat menghadapnya. Aku bisa melihat bagaimana bola mata hitamnya menatapku dengan dalam dan … mengintimidasi.
“Kamu mau naik gunung sama Rifki, sedangkan kamu tahu aku aja gak pernah ngajak kamu ke Gunung?” Oh, Ya. Suara Nino memang lembut, tapi suara Nino yang seperti itu selalu berhasil mengintimidasiku.
“Loh, salah kamu gak pernah kasih aku ikut. Padahal cuma Gunung.” Dengan kesal aku membalikan badan dan kembali menghadap ke depan. Lampu taman yang padam seolah hidup dengan tiba-tiba dan menertawaiku detik itu juga. “Padahal aku cuma minta naik gunung. Gimana kalau aku minta sebrangin Samudera Hindia?”
Aku bisa mendengar bagaimana Nino berdecak kesal. Dua tahun menjadi pacarnya membuatku bisa menebak jika sekarang Nino sedang memendam amarahnya. Jarang sekali Nino marah-marah padaku apalagi sampai main tangan. Padahal aku tahu, selain posesif dan pencemburu, Nino juga orang paling jago marah.
“Pokoknya aku gak kasih kamu ikut.”
“Yaudah, kalau gitu aku ikut kamu ke Pangrango bulan depan!”
Oh, tentu saja aku tidak mau kalah. Cukup ya, aku ditingal-tinggal Nino naik-turun gunung selama ini.
“Gunung Pangrango bukan playground, Gita.”
“Dan Aku bukan ayunan yang bisa kamu mainin, terus ditinggal pergi gitu aja.”
***
Setelah perdebatan singkat di Taman Kampus Teknik tempo hari, Nino ngambek dan tidak mengabariku sampai saat ini. SMS yang dikirimkannya padaku hanya berisi peringatan agar aku tidak lupa makan teratur dan membawa jaket kemanapun.
Duh, Kok rasanya seperti mau ditinggal pergi jauh ya.
Tapi saat ini aku sudah berada di sekertariat Sanggamara. Ada beberapa laki-laki berambut gondrong dengan kumis atau janggut tipis di depannya. Jelas aku tidak tahu siapa mereka. Aku hanya mencari keberadaan Rifki yang sudah berjanji akan menungguku di sini.
Sekertariat ini benar-benar terlihat ramai, aku tidak bisa melihat dimana Rifki saat ini. Apakah berada diantara laki-laki di atas motor-motor yang terpakir di depan sekertariat, atau diantara laki-laki dengan golok yang digunakan untuk membuat pancu di sudut bagian lain bangunan ini.
Yang jelas aku sudah menghubunginya, dan tidak mendapatkan jawaban.
“Nyari siapa, Mbak?”
Tiba-tiba aku dikejutkan oleh seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan berkumis tipis yang akan melewati pagar dengan motor bebeknya.
“Nyari Rifki. Udah janjian di sini, Kok.”
“Oh, masuk aja dulu, Mbak. Tadi Rifki keluar sebentar.”
Apa? Masuk ke dalam katanya? Lalu berkumpul bersama semua laki-laki setengah menyeramkan di sana? Ih, kok aku mikir seribu kali ya. Kayaknya mending di sini saja. Lagian, orang ini kan bilangnya Rifki Cuma sebentar.
“Enggak, Makasih. Biar di sini saja.”
Aku sama sekali tidak melihat penampakan anak perempuan seusiaku di dalam. Sama sekali tidak ada, padahal di Gahara –Klub pecinta alam kampusku, banyak sekali mahasiswi perempuan yang sering ikut mendaki. Untuk itulah aku juga ingin ikut, tapi sialnya Nino tidak pernah mengijinkan.
Dari tempatku sekarang, aku hanya melihat seorang perempuan di balik gorengan-gorengan hangat yang banyak disantap anak-anak Sanggamara. Dari pakaiannya sudah bisa ditebak kalau dia hanya pedangan gorengan atau sejenisnya. Bukan anggota atau apa.
Setelah beberapa kali melirik jam tangan hadiah dari Nino, akhirnya Rifki datang. Dia mengenakan jaket Avtech dan slayer Sanggamara berwarna ungu yang malah mengingatkanku pada kumpulan anak slankers jaman dulu.
“Sori, Git. Lama ya?” Rifki datang dengan motor. Dan ketika melihtaku di depan pagar, anak itu langsung turun. Bau badannya tidak sedap. Seperti bau Nino setelah bermain Futsall atau lari pagi. “Tadi abis dari senayan, liat anak-anak yang pada latihan.”
“Naik yok. Kita masuk.”
Dengan ragu Aku naik diboncengan motor Rifki. Motornya Kawasaki Ninja yang knalpot motornya benar-benar membuat polusi suara.
“Kita Registrasi dulu.” Katanya, setelah turun dari motor dan berjalan melalui laki-laki dengan golok tadi. Banyak suara yang usil mengomentari kebersamaanku dengan Rifki. Belum lagi siulan-siulan usil dari sudut lain. Ih, kok mereka rese sih.
Sekertariat Sanggamara jauh lebih besar dibandingkan dengan sekertariat Gahara di Kampus. Ada cukup banyak Sofa di dalam dan sebelum aku masuk ke ruangan registrasi, aku bisa melihat bagaimana sebuha foto besar terpampang di bagian dinding kosong yang tereskpos. Foto besar itu berisi kurang lebih lima puluh orang yang aku yakin anggota Sanggamara. Belum lagi foto-foto lain mereka, seperti foto ketika berada di Puncak Gunung Mahameru, Semeru, bahkan Jayawijaya. Aduh, sepertinya mereka sudah malang melintang. Aku jadi Keki sendiri.
“Sore, Bang Opi.”
Seorang laki-laki berusia pertengahan tiga puluh berada di balik meja dengan kemeja kotak-kotaknya yang rapi. Berbeda sekali dengan anak laki-laki yang bergerombol diluar tadi, yang berkeringat dan berjanggut.
“Eh, Ki. Sama siapa?”
“Temen, Bang. Mau ikut Ke Cikuray katanya.”
Rifki memegang sikutku dan menuntunku untuk duduk di depan Bang Opi. Dia juga ikut duduk, di kursi lain di sampingku. Aku tersenyum canggung pada sosok Bang Opi yang ramah.
“Wah, Mbak siapa nih namanya?”
“Panggil Gita aja, Bang.” Aku sedikit bergerak mengatur duduk.
“Yakin mau ikut Mendaki santai?”
Duh, ini adalah bagian yang paling tidak kusukai. Basa-basi. “Yakin, Bang. Cuma ya, Aku masih pemula. Belom pernah naik Gunung.”
“Gak apa-apa. Toh nanti juga Dek Gita gak bakalan sendiri. Cuma, sebelum registrasi kita perlu memberitahu tentang berbagai persiapan yang harus dilakukan sebelum naik.” Bang Opi terlihat menunduk, mengorek isi laci dan mengeluarkan sebuah formulir lalu meletakannya di depanku. “Jadi, pertama-tama Dek Gita harus menyetujui tentang sejumlah biaya yang harus dibayarkan setelah registrasi, setelah itu ada cek kesehatan dari tim medis kami, Latihan fisik secara berkala, lalu kembali cek kesehatan dan terakhir persiapan dan pengumpulan barang dan logistik.”
Aku hanya mengangguk-anggukan kepala dan tersenyum masam mendengar apa saja yang harus dilakukan sebelum naik ke gunung. Mana ada cek kesehatan pula, kalau aku ketahuan punya asma dan mereka tidak mengijinkanku naik bagaimana?
“Iya, Bang. Berarti formulirnya saya bawa ke Rumah ya?” Aku melihat ada kolom tandatangan orangtua atau wali, jadi ya sudah pasti pengisian formulirnya dibuat PR.
Aku sih sudah yakin Mama dan Papa akan mengijinkanku, tapi tidak dengan Nino. Dan Bagian paling sulit adalah memberitahunya tentang hal ini.
***
Celaka dua belas adalah ketika Nino sudah berada di ruang tamu rumahku, sedangkan aku baru kembali ke rumah sekitar pukul setengah enam sore. Dengan tidak biasa Nino bercengkrama dengan Mama, kalau tidak salah dengar, mereka membicarakan masalahcupcake yang berbulan-bulan lalu aku buat untuk Nino. Ih, seperti tidak ada bahan obrolan lain saja.
“Gita. Kamu dari mana saja. Nino udah nunggu lama, kamu malah baru pulang.” Mama berdiri dan menghampiriku yang masih membeku ditempat. Tidak percaya Nino akan datang menungguku. Jantungku berdetak cepat, rasanya seperti ketika diapelin pertama kali. “Dih, mana bau lagi. Malu ih.”
“Bau-bau juga, tetep anak Mama.” Aku melangkah ke arah sofa dan duduk tepat disebrang Nino. Ekspresi wajahnya jauh lebih baik dibanding terakhir kali aku melihatnya. “Hai.”
Aku mulai menyapanya duluan, dan setelah itu Mama melenggang pergi, seolah sadar diri bahwa ini adalah urusan anak muda.
“Hai. Kok baru pulang? Dari mana?”
“Kok, tumben dateng? Ada apa?”
Tanpa kusangka Nino malah menertawaiku yang malah balik bertanya dibandingkan menjawab pertanyaannya. Mana sepertinya nada bicaraku sarkastis sekali, padahal sama pacar sendiri.
“Emang harus ada apa-apa ya, kalau mau dateng?”
“Ya, gak biasa aja. Kamu kan pacar tersibuk abad ini.”
Nino menatapku lembut, tangannya yang sedari tadi tersimpan di pangkuan kini terulur menyentuh kedua tanganku yang bebas. Ah, rasanya sudah lama sekali kami tidak seperti ini.
“Aku minta maaf, Ya. Kalau selama ini belum bisa jadi pacar yang baik buat kamu.” Suara Nino memang lembut, tapi jelas tidak pelan. Dan aku yakin Mama sedang menguping entah dimana.
“Jujur aja, aku gak bisa ngambek-ngambekan lama sama kamu. Rasanya gak enak.” Ya, sama. Memangnya aku suka didiemin seperti lukisan di museum? Tapi aku hanya mengangguk dan memaklumi kelakuan Nino. Aku yakin Nino hanya terlampau sayang padaku dan tidak menginginkan hal buruk terjadi padaku. Ya, Aku mengerti …
“Tapi, Aku tetep gak bisa ijinin kamu naik gunung bareng Rifki.”
Loh kok? Bibirku yang semula tersenyum maklum nan lembut berubah cemberut kembali. Apa-apaan Nino ini? aku kira dia sudah sadar telah bersikap posesif padaku lalu mengijinkan aku pergi.
“Kok gitu sih?” Jelas saja aku tidak terima.
“Kamu harus inget, Git. Kamu cewek, punya Asma pula. Aku sudah tanya ke Rifki, kalau agenda Sanggamara selanjutnya itu Ke Cikuray. Bahkan aku gak yakin kamu tahu Cikuray dimana.” Memang iya sih. Aku belum tahu dimana letak Gunung Cikuray yang dimaksud Rifki dan Bang Opi tadi, aku baru akan mencari tahunya setelah ini.
“Kamu tahu berapa tinggi Cikuray?” Jelas aku menggeleng, Cikuray dimana saja aku tidak tahu, apalagi ketinggiannya. “Dua ribu delapan ratus dua puluh satu meter diatas permukaan laut.” Aku hampir saja terngaga mendengar perkataan Nino. Serius? Meskipun aku yakin ketinggiannya masih kalah jauh dengan ketinggian Mahameru, tapi … tetap saja aku tidak bisa membayangkan seberapa tinggi si Cikuray.
“Belum lagi kondosi alamnya yang masih liar. Masih banyak Babi hutan, binatang buasnya juga.”
“Serius?” Kali ini aku benar-benar tidak bisa menahan ketercenganganku. Dan aku bisa melihat bagaimana Nino tersenyum melihat kepanikanku saat ini. Kenapa aku bisa keceplosan norak seperti itu sih.
“Iya. Makanya aku gak kasih ijin kamu ikut ke sana.”
Jujur saja aku bingung. Bagiamana aku harus mengelak lagi dan tetap bersikukuh dengan kehendakku sendiri, sedangkan aku sendiri mulai tidak yakin dengan keputusanku.
“Kalaupun kamu tetep mau naik Gunung, kamu cuma boleh naik bareng aku, gak sama Rifki apalagi tanpa aku.”
Kali ini aku totoal speechless. Sebenarnya aku juga seperti itu. Aku ingin pergi hanya dengan Nino. Tadinya aku hanya ingin menggertak Nino saja, tidak benar-benar ingin pergi tanpanya.
“Besok kamu ikut aku ya. Aku mau ngasih tunjuk kamu sesuatu.”
***
Nino benar-benar membawaku pergi di pagi-pagi buta keesokan harinya. Dia datang dengan Avanza Papanya. Tumben, padahal Nino paling anti bawa mobil orang.
Di sampingnya, aku hanya bisa duduk sambil melihat bagaimana jalan tol jagorawi yang lembab. Oh, Ya. Tadi malam sempat hujan dan sampai saat ini masih gerimis. Kaca mobil juga berembun.
Sampai saat ini aku belum tahu akan dibawa kemana. Aku tidak terlalu memikirkannya, aku hanya butuh tidur lagi saat ini.
“Aku tidur dulu boleh gak, No?” Suaraku masih seperti teredam bantal, padahal aku sudah mandi air dingin tadi.
Kulihat Nino menolehkan kepala ke arahku, yang hanya kusambut dengan pandangan sayu ala orang mengantuk.
“Aku nyalain CD ya? Mau lagu apa?”
“Apa aja asalkan jangan koleksi lagu kamu.” Kenapa? Karena koleksi lagu Nino itu tidak ada yang benar. Dia pecinta Eminem, yang kalian tahu musiknya berisik.
“Tenang, ini kan mobil Papa. Aku pasangin Glen Fredly ya.”
Aku hanya mengangguk sambil merapatkan jaket yang kukenakan. Entah anggukanku terlihat oleh Nino atau tidak, Aku tidak peduli. Aku hanya ingin tidur …
***
Dan aku terbangun lalu menyadari aku sudah tidak berada di Jakarta. Glen Fredly masih bernyanyi, dan ketika aku melihat Nino, dia hanya melemparkan senyumannya ke arahku. Duh, manis sekali.
Saat kulihat jalanan di depan, Avanza silver ini berada di antara pertigaan lalu berbelok ke kanan.
“Ini di Paragajen.”
Hah? Dimana itu?
Dan saat aku menolehkan kepala ke arah jendela, aku bisa menemukan Papan nama Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di sebelah kiri jalan, terpampang besar dan semakin membuatku bertanya-tanya.
“Jaketnya dipake yang bener. Di sini dingin tahu.”
Aku menurutinya, memperbaiki kondisi jaketku yang agak berantakan pasca tidur sedari tadi. Banyak pohon-pohon besar disekitar jalan, selain jalan menanjak dan berliku aku cukup dibuat takjub dengan keadaan disekitarnya. Mana bisa aku melihat yang seperti ini di jalan Jakarta.
Lalu, kira-kira tiga kilo meter dari Paragajen yang dikatakan Nino tadi, mobil sampai di portal pintu gerbang gerbang wisata Cibodas. Aku bisa tahu karena memang ada plang besar di portal itu.
Nino membayar sejumlah uang retribusi yang tidak seberapa untuk kami berdua lalu kembali melaju. Tidak lama kemudian aku menemukan sebuah bangunan, seperti kantor daerah atau apa. Aku tidak tahu.
“Kita berhenti di sini.”
Loh kok?
Tapi, betapapun aku kebingungan dengan apa yang terjadi hari ini. Aku sama sekali tidak mengajukan protes. Sedari tadi, aku hanya mangut-mangut dan iya-iya aja dibawa kemanapun oleh Nino.
Nino membantuku berjalan, seolah aku adalah penderita lumpuh atau gangguan saraf. Tapi memang sepertinya aku lumpuh seketika keluar dari mobil. Entah ini efek duduk terlalu lama atau dingin yang benar-benar menusuk.
Ada danau di depan kantor ini. Entah ini sebenarnya memang Kantor atau Villa. Bangunannya nyaman.
“Sini, duduk.”
Nino mengajakku duduk di salah satu bangku disamping bangunan itu, lalu benar-benar menemukan sebuah pemandangan menakjubkan. Sebuah Gunung, yang dari jarakku saat ini berwarna biru, membuatnya terkesan sangat jauh dan tak tergapai.
“Ini Kantor Besar taman nasional gunung Gede Pangrango.”
Apa katanya? Aku terngaga. Jadi aku berada di pintu masuk ke gunung Gede Pangrango? Serius? Ih, kok Nino gak bilang-bilang sebelumnya.
“Dan kita lagi di Cibodas sekarang. Puncak Gede atau Pangrango masih jauh. Jauh banget. Kamu liat di sana kan?” Nino menunjuk gunung dihadapan kami. Ya, memang tidak terlihat dekat. Kakiku mendadak lemas membayangkan jika setelah ini aku diajaknya mendaki.
“Kamu tahu gak, kenapa aku gak pernah ngajak kamu ke Gunung, padahal banyak cewek lain yang aku bolehin ikut di acara Gahara?”
Tiba-tiba suara Nino benar-benar melunak. Kami sudah berhadapan saat ini, tangannya menggenggam kedua tanganku. Aku kembali dibuat luluh.
“Karena kamu adalah orang yang aku sayangin, dan aku sama sekali gak mau orang yang aku sayangin kenapa-napa.” Aku hanya balas mendalami danau yang ada di bola matanya, seolah bersenang-senang di sana dan sedikit mengintip apa yang di tatap Nino melalui dua bola matanya.
“Seperti yang aku bilang, Gunung itu bukan Playground. Tapi aku sama sekali gak pernah nganggep kamu seperti ayunan. Kamu adalah kamu, orang yang aku sayang.”
Tanpa bisa dibendung lagi, air mataku jatuh dan membentuk aliran di sepanjang pipiku. Jari-jari tangan Nino mengusapnya dan membuat aku berhenti terisak.
“Aku cuma bisa nunjukin ini sama kamu.”
“Kamu gak percaya aku bisa sampai sana dengan selamat?” Ujung jari telunjukku terangkat dan menunjuk bagian pucak gunung yang terlihat seperti rendah dari tempatku saat ini.
“Bukan. Aku bukannya gak percaya sama kamu. Aku gak percaya kalau aku bisa jaga kamu dengan baik.”
Dan detik itu juga aku menangis. Hujan yang semula hanya turun dengan malu-malu tiba-tiba saja turun dengan deras. Kami tetap ditempat, aku tetap menangis, dan Nino setia menghapus air mataku.
Aku malu karena menangis didepan gunung yang berdiri dengan kokoh dan pongah di sana, aku malu karena aku membuat Nino tidak percaya pada dirinya sendiri.
***
Ehem, ada yang harus diluruskan tentang Deskripsi Kantor Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrarngo diatas, karena aku gak tau gimana wujud aselinya, aku cuma berusaha mendeskripsikannya sesuai dengan apa yang aku lihat di gambar ya ^^ jadi maaf kalau ada ketidaksesuaian.
Silahkan Layangkan komentar di kolomnya ya. Love you, Gais {}
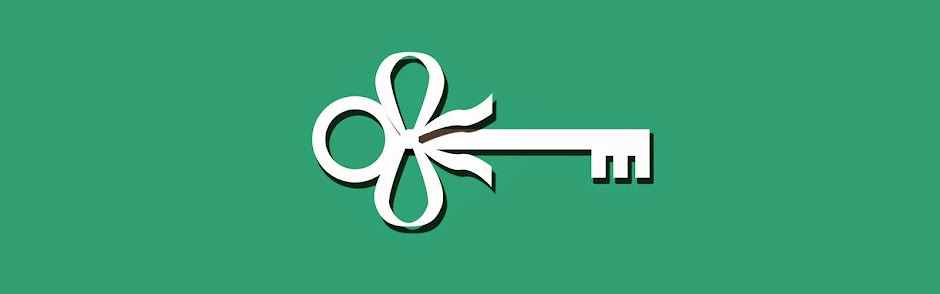












aku gak nyangka kamu se-so-sweet ini, maronah :')) bagus ceritanya :D aku pengen jadi gita :((
BalasHapusKamu mimpi aja kalo mau jadi Gita dalam sekejap. Atau cari doi baru yang kayak Nino :3 Thanku udah baca yaaa *ketjup*
HapusCerita kayak gini mungkin bisa dipanjangin terus dijadiin novel, terus dikirim ke penerbit, terus kalau lolos jadi terbit, udah gitu aja. Kalo terus lagi nanti malah nabrak huahaha
BalasHapusBisa terbit, Aamiin. Terus-terus aja kayak tukang parkir :v Thanks udah mampir dan baca ya *ketjup* eh
Hapus